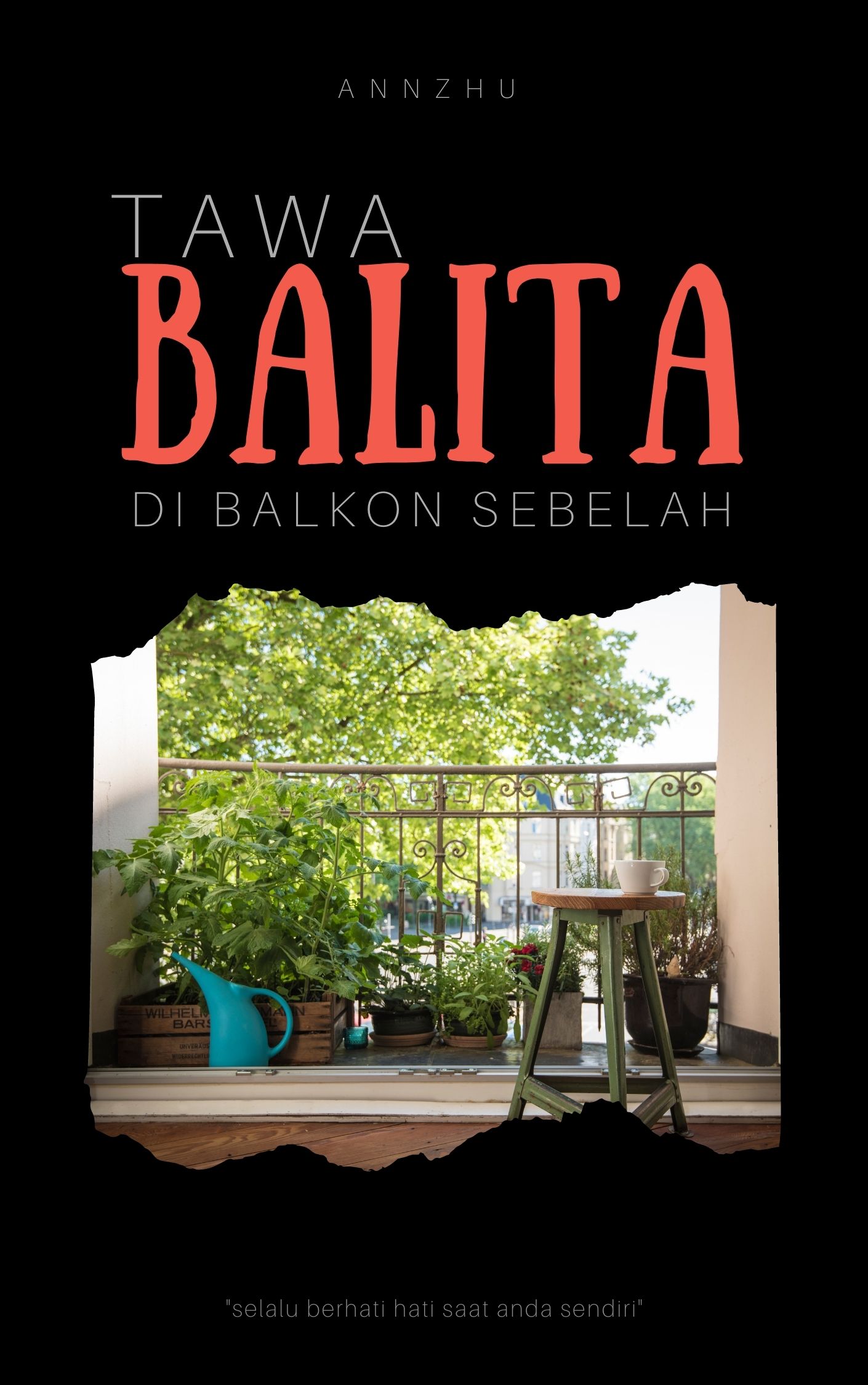Lebaran datang lagi. Suasana hangat, suara takbir, aroma ketupat, dan tawa keluarga—semua masih sama. Tapi ada yang hilang. Ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapa pun: Mama dan Papa. Tahun-tahun tanpamu selalu terasa ganjil, tapi tahun ini… entah kenapa, lebih sepi dari biasanya.
Entah karena lelah menyimpan, atau mungkin karena rindu yang terlalu lama tak tersampaikan. Rasanya seperti duduk di ruang tamu yang pernah penuh tawa, kini hanya ada bayang-bayang kenangan. Di balik setiap senyum yang kupaksakan di hari raya, ada tangis yang kutahan. Aku berusaha tetap terlihat kuat di depan anakku, keluargaku yang kecil. Tapi hatiku, selalu mencari rumah yang dulu. Rumah itu bukan sekadar tempat—itu Mama dan Papa.
Aku masih punya uwa, om, tante. Masih ada keluarga yang tersisa. Tapi langkahku terasa berat, seperti ada pintu yang tak berani aku ketuk. Bukan karena tak ingin bersilaturahmi, bukan. Tapi ada ketakutan yang diam-diam tumbuh. Takut dianggap salah, takut disambut dingin, takut mereka berpikir, “Ah, pasti mau minjem uang lagi.”
Padahal aku cuma ingin datang, duduk sebentar, menyapa, mengucap maaf lahir batin. Tapi bayangan penolakan membuat jemari tak sanggup sekadar mengirim pesan. Aku terjebak antara rindu dan rasa bersalah. Aku tahu pernah ada masa aku datang membawa beban—bukan kabar bahagia. Tapi aku juga ingin dikenal bukan karena itu saja.
Aku bukan orang yang sempurna. Aku jatuh, pernah terpuruk, dan ya… pernah meminta tolong. Tapi aku juga bangkit, berjuang, dan belajar banyak hal. Aku belajar jadi ibu, jadi perempuan yang lebih kuat, meski kadang merasa sangat sendirian. Aku hanya ingin sekali saja bisa datang ke pelukan yang hangat tanpa ada rasa curiga di udara. Aku ingin datang sebagai aku—yang rindu, bukan yang meminta.
Kadang aku menatap langit dan berbisik, “Mah, Pah… aku rindu. Aku rindu rumah yang tak menghakimi, pelukan yang tak bertanya macam-macam. Aku rindu disambut karena aku adalah aku.” Aku ingin kalian tahu, bahwa rindu ini tak pernah hilang. Bahwa kepergian kalian meninggalkan ruang yang tak tergantikan.
Aku tahu, waktu terus berjalan. Aku tahu, semua orang punya beban masing-masing. Tapi… kenapa ya, rasanya sepi ini makin hari makin besar? Mungkin karena aku terlalu lama diam, terlalu takut disalahpahami. Mungkin karena aku tak tahu lagi bagaimana caranya membuka pintu yang dulu begitu akrab.
Aku takut. Takut mereka tak ingin lagi melihatku. Takut mereka merasa aku hanya datang saat butuh. Takut kalau senyumku dianggap pura-pura. Tapi di sisi lain, aku juga ingin percaya… bahwa mungkin mereka juga rindu. Mungkin mereka juga menanti. Mungkin… semua hanya soal keberanian.
Jika nanti keberanianku tumbuh, semoga yang kudatangi masih bersedia membuka pintu. Dan jika tidak… semoga Allah tetap menjagaku dari rasa putus asa, dan menjaga hatiku agar tetap lembut, walau kadang terasa sangat sepi.
Lebaran ini mungkin aku hanya bisa mengirim doa. Doa untuk Mama dan Papa, yang semoga di sana, senantiasa damai. Doa untuk diriku sendiri, agar tetap kuat dan berlapang dada. Doa untuk mereka yang masih ada, agar hatinya terbuka.
Dan jika suatu hari nanti, anakku bertanya kenapa lebaran kita sepi, akan aku ceritakan. Bahwa kadang, menjadi dewasa berarti belajar menahan rindu tanpa bisa selalu mewujudkan temu. Kadang, menjadi orang tua berarti tetap tersenyum meski hati ingin berlari pulang.
Aku akan mengajarkannya mencintai keluarga, meski tak selalu bisa dekat. Aku akan membesarkannya dengan keyakinan bahwa silaturahmi adalah tentang hati yang tulus, bukan hanya tentang jarak dan jamuan. Dan aku akan berusaha menjadi rumah, agar ia tak perlu merasa seperti aku merasa hari ini.
Untuk Mama dan Papa… kalian tetap rumahku. Selamanya. Untuk uwa, tante, dan om… jika kalian membaca ini suatu hari nanti, ketahuilah, aku tidak pernah melupakan kalian. Hanya saja, aku sedang mencari keberanian untuk datang, bukan dengan tangan kosong, tapi dengan hati penuh rindu.
Selamat lebaran. Maaf lahir dan batin, dari anak yang rindu, tapi juga takut.